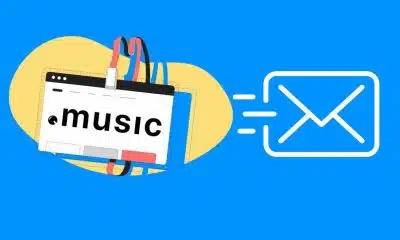Articles
Tigapagi dan Sebuah Ambisi Sunyi

- Share
- Tweet /srv/users/gigsplayv2/apps/gigsplayv2/public/wp-content/plugins/mvp-social-buttons/mvp-social-buttons.php on line 66
https://gigsplay.com/wp-content/uploads/2014/09/tigapagi.jpg&description=Tigapagi dan Sebuah Ambisi Sunyi', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Pin This Post">
Plaza Desain 2014; Galeri 678, Kemang, Jakarta; Minggu, 21 September 2014
Jika seorang sedang menunggu pertunjukan Tigapagi, terlebih jika ia sebelumnya mengetahui (dan menghayati) siapa itu Tigapagi, mungkin bisa dimaafkan jika ia menginginkan agar lampunya segera dimatikan. “Biar ngena sama konsep mistis ala 60 an” mungkin adalah kalimat yang terlontar darinya tanpa harus banyak berpikir. Disinilah letak kepiawaian Tigapagi sebagai grup musik, setidaknya sebagai perwujudan konsep terlebih dahulu, bagaimana khalayak banyak masih memiliki alasan untuk percaya kalau musik Indonesia belum takabur dari konsep—Tigapagi-lah alasannya.
Mudah rasanya untuk bilang kalau semua itu hanya perisai dari musik medioker yang, seperti layaknya ekspresi, bisa dimaafkan karena “konsep+kostumnya ada nih.” Tigapagi pun dipenuhi oleh perkiraan demikian: Membuat album kontemporer dengan 14 lagu yang terus menyambung tanpa henti? Sudah. Mengenalkan pendengar pada album bertajuk Roekmana’s Repertoire dan cenderung bersikap elusif dan acuh tak acuh terhadap pertanyaan “siapa itu Roekmana”? Beres. Dari segi semua ini, Tigapagi bisa dibilang sebagai grup musik yang dilahirkan dan dibesarkan oleh sebuah tema.
Tapi kenyataannya bukan demikian. Grup musik asal Bandung yang digawangi oleh Sigit Pramudita (vokal/gitar/theremin), Eko Sakti Oktavianto (gitar/piano) dan Prima Dian Febrianto (gitar) menciptakan musik pentatonik cantik yang justru melampaui konsep waujubilah yang bisa saja mengancam keotentikan musik mereka sendiri. Artinya, Tigapagi tidak sekedar tampang saja, melainkan segerombol teman yang memiliki talenta dalam bermusik dan sadar betul akannya. Dalam perhelatan yang diselenggarakan oleh DKV Universitas Bina Nusantara di Galeri 678, Kemang, Tigapagi membuktikan semua ini—memainkan set yang singkat dan apik; hanya dilengkapi dua biola dan satu celo dan interaksi minim dengan penonton.
Lagu lagu dari album pertama mereka dinyanyikan dengan syahdu dan fokus seperti pembuka Yes We Were Lost in Our Hometown, S(m)unda, Tangan Hampa Kaki Telanjang, Pasir, Vertebrae Song, Alang-Alang, sampai penutup Batu Tua. Alunan musik gitar pentatonik berdarah folk Sunda—tanpa terkesan seperti musik etno—dimainkan secara teliti dan rapi dan efeknya bisa dilihat dari raut muka serius dari sebagian penonton. String-section, sebelumnya sempat dikritik karena terlalu lantang, dimainkan secara hati-hati—menjadikannya lebih sebagai komplemen, bukan lawan.
Mungkin Tigapagi—atau siapapun yang bergema di kancah musik Indonesia—bisa menolak adanya fanboyisme kelewatan seperti halnya fanboyisme saya kepada musik Tigapagi saat Roekmana’s Repertoire dirilis tahun lalu. Semua tema itu bisa dianggap biasa aja sih ataupun musik yang cenderung dianggap ambisius mungkin bisa ditolak mentah-mentah—diketawain mungkin. Seperti yang dibuktikan oleh performa mereka Sabtu kemarin, keotentikan dan kecantikan musik Tigapagi bisa menembus kesadaran dari apa yang terdengar dibawah, bukan diatas.
Oleh: Stanley Widiarto